Demokrasi Anarki
Tindakan anarkistis
menyusul Pemilukada Kota Palopo, Sulawesi Selatan, membersitkan sisi
kelam dari demokrasi kita. Ruang kebebasan yang dimungkinkan demokrasi
digunakan untuk membunuh nilai-nilai demokrasi.
Kekerasan adalah musuh utama demokrasi, bertentangan
dengan spirit dan substansinya. Tak lain karena demokrasi sebagai jalan
hidup (way of life) dengan seperangkat institusinya merupakan suatu
sarana nonkekerasan.
Di bawah kondisi-kondisi demokratis, kekuasaan dan
kepentingan tidak bisa diperoleh melalui jalan pemaksaan, melainkan
melalui jalan konsensus yang memerlukan penghormatan publik pada orang
lain yang setara meskipun berbeda.
Demokrasi juga merupakan suatu sistem pembagian
kekuasaan secara legal yang aktor-aktornya sama-sama menghindari bahaya
kekerasan dan sama-sama diuntungkan oleh ketiadaan kekerasan.
Ekspresi kekerasan di Palopo dan juga daerah lainnya di
Tanah Air mengindikasikan bahwa kecepatan perubahan prosedur dan
kelembagaan demokrasi tak seiring dengan kecepatan perubahan budaya
politik. Perubahan budaya politik memang perkara yang paling muskil dan
lambat dalam transformasi menuju masyarakat demokratis, karena
melibatkan perubahan mendasar dalam tata nilai yang tidak bisa
diarahkan secara efektif oleh elite penguasa dalam tempo singkat.
Akan halnya di Indonesia, kesulitan perubahan budaya
politik ini dipersulit oleh konsentrasi yang berlebihan pada perubahan
aspek-aspek prosedural dengan mengabaikan perhatian pada proses
pembelajaran masyarakat.
Elite dan partai politik hanya sibuk melakukan
perubahan aturan main demi kepentingannya sendiri, melupakan fungsi
pendidikan politik dan kapasitas rakyat untuk menyesuaikan diri dengan
perubahan tatanan tersebut.
Dalam pada itu, betapa pun demokrasi telah membawa
keterbukaan ruang publik yang memungkinkan pengartikulasian beragam
kepentingan, tidaklah berarti bahwa suara-suara publik itu otomatis
mendapat akses pada proses pengambilan keputusan. Penjelimetan prosedur
demokrasi menyuburkan isu politik yang membuat rezim pemberitaan harus
berkejaran dengan perputaran isu yang berganti cepat.
Akibatnya, perhatian publik pada isu tertentu sulit
mengalami pengendapan dalam tempo yang relatif lama karena bisa segera
dilibas oleh isu lainnya. Situasi ini memberi angin bagi para perumus
kebijakan yang cenderung narsistis untuk lebih mengurusi agenda
kepentingannya sendiri, dengan mengabaikan perhatian pada aspirasi
publik.
Terjadinya kemampatan transformasi aspirasi dari ranah
publik ke ranah kebijakan memberi peluang bagi proses dagang sapi dalam
penyusunan prioritas kebijakan dan perundang-undangan. Kebijakan
pemekaran wilayah merupakan lahan yang sarat transaksi seperti itu.
Dalam banyak kasus, pengabulan pemekaran tidaklah didasarkan pada
tingkat urgensi atas pertimbangan strategisnya, melainkan oleh tingkat
“kecanggihan” deal maker-nya.
Perkembangan cepat dalam proses pemekaran wilayah
merangsang elite-elite lokal yang kalah bersaing dalam wilayah politik
lama untuk memperjuangkan pemekaran. Dirangsang oleh preseden
irasionalitas izin pemekaran sebelumnya, elite-elite ini pun kerapkali
datang tanpa kalkulasi yang masuk akal dan bisa saja menggunakan
aksi-aksi irasional dalam memaksakan kehendaknya. Dengan kata lain,
aksi irasionalitas kekerasan dalam kasus Sumatera Utara itu merupakan
arus balik dari kebijakan-kebijakan irasional yang dikeluarkan oleh para
pembuat kebijakan sebelumnya di seantero negeri.
Oleh karena itu, demokrasi sebagai cara menyelesaikan
masalah publik tanpa jalan kekerasan hanya bisa dipertahankan dengan
memuliakan akal sehat dan pertanggungjawaban. Politik sebagai sarana
menyelesaikan masalah kolektif harus dibebaskan dari tawanan
kepentingan elitis menuju kemaslahatan hidup bersama, di mana kebebasan
hanya memperoleh kemuliaannya dengan bertanggung jawab kepada yang
lain.
Untuk itu, demokrasi lebih dari sekadar ledakan
kebebasan dan penjelimetan prosedural, melainkan juga suatu
transformasi dalam proses belajar kolektif. Secara perlahan, masyarakat
harus dibawa keluar dari ikatan-ikatan komunal yang tertutup menuju
asosiasi-asosiasi yang terbuka. Di dalam asosiasi, syarat keanggotaan
tidaklah ditentukan oleh latar primordialnya, melainkan oleh kapasitas
individualnya.
Hal ini merupakan prasyarat bagi kehidupan kenegaraan
dan kewargaan yang baik. Bahwa keanggotaan dan kepemimpinan dari suatu
unit lembaga kenegaraan tidaklah didasarkan oleh latar primordial,
seperti putra daerah, melainkan oleh kemaslahatan dan kapasitas
warganya. Dalam konteks bernegara, warga masyarakat harus
bertransformasi menjadi warga negara yang memiliki kedudukan yang sama
di depan hukum.
Oleh karena itu, demokrasi yang baik memerlukan
pendidikan kewarganegaraan yang baik. Bahwa manusia dan warga
masyarakat yang baik tidaklah dengan sendirinya menjadi warga negara
yang baik. Untuk menjadi warga negara yang baik, pemimpin dan kebijakan
negaranya sendiri harus baik berkelindan dengan kapasitas warganya untuk
menyadari hak dan kewajibannya.
Kita telah memiliki perangkat keras demokrasi, tetapi perangkat
lunaknya masih tetap tirani. Marilah kita belajar berdemokrasi dengan
memuliakan nilai-nilainya!*** Creatif by: Teguh_Haluan
by:Yudi Latif

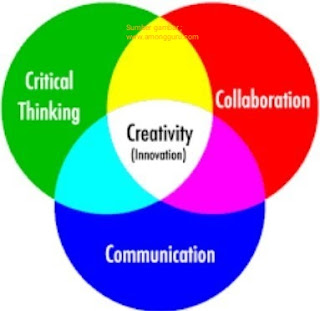

Komentar
Posting Komentar